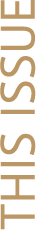Lima Penulis Tiongkok Mampir di Jakarta
 Di masa Revolusi Kebudayaan, dalam upaya menghapus kelas dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, Mao Tse Tung membentuk unit-unit paramiliter dan mereka ini mengartikan revolusi sebagai tindakan merusak artefak museum, buku, barang antik, lukisan dan berbagai benda seni sebagai praktik. Tiongkok mengalami satu era yang mengguncang peradabannya di masa Mao memimpin. Wabah kelaparan dan pembunuhan berlangsung di mana-mana untuk pemurnian sosialisme dengan cara Mao. Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir di Tiongkok pada 1980-an, para penulis yang mengalami masa tersebut melakukan refleksi tentang masa itu dan menulis karya-karya yang dikategorikan sebagai “sastra luka”. Sekarang Tiongkok mengalami fase baru. Di dunia kesusastraan, para penulis memiliki tema-tema lebih beragam dan luas untuk diwujudkan dalam karya mereka.
Di masa Revolusi Kebudayaan, dalam upaya menghapus kelas dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, Mao Tse Tung membentuk unit-unit paramiliter dan mereka ini mengartikan revolusi sebagai tindakan merusak artefak museum, buku, barang antik, lukisan dan berbagai benda seni sebagai praktik. Tiongkok mengalami satu era yang mengguncang peradabannya di masa Mao memimpin. Wabah kelaparan dan pembunuhan berlangsung di mana-mana untuk pemurnian sosialisme dengan cara Mao. Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir di Tiongkok pada 1980-an, para penulis yang mengalami masa tersebut melakukan refleksi tentang masa itu dan menulis karya-karya yang dikategorikan sebagai “sastra luka”. Sekarang Tiongkok mengalami fase baru. Di dunia kesusastraan, para penulis memiliki tema-tema lebih beragam dan luas untuk diwujudkan dalam karya mereka. Lima penulis Tiongkok, Feng Yi, Yang Ke, Yuan Min, Pan Xiang Li dan Liu Xianping, yang hadir di Serambi Salihara pada malam 27 April 2013 itu untuk membaca karya dan berdiskusi menampilkan kecenderungan tersebut. Dua sastrawan Indonesia dan sekaligus para kurator Komunitas Salihara, Nirwan Dewanto dan Sitok Srengenge ikut membacakan karya. Dalam diskusi yang melengkapi ajang baca karya tersebut, penyair Yang Ke, salah satu dari lima penulis Tiongkok itu, menyatakan bahwa dirinya menulis tentang apa yang terjadi di luar dirinya dan tentang apa yang ada di luar dirinya, yang katanya membedakan puisinya dengan puisi Sitok Srengenge dan Nirwan Dewanto, yang mengungkap tentang apa yang ada di dalam diri. Yang Ke membaca dua sajaknya, Sepetak Sawah di Dongguan dan Rakyat.
Ketika para sastrawan Tiongkok ditanya tentang Mo Yan, pemenang Nobel Sastra 2012, Yang Ke menjawab bahwa banyak sastrawan yang menulis sebagus Mo Yan di negerinya. “Tapi Mo Yan juga memimpin dari segi kuantitas. Ia telah menerbitkan 10 novel,” tutur Yang Ke. Sebelum Mo Yan meraih Nobel, perhimpunan penulis di provinsinya menganugerahi Mo Yan penghargaan sastrawan seumur hidup. “Dalam negeri sendiri ada yang mengatakan bahwa Mo Yan tidak pernah menyuarakan kritiknya, Tapi sebenarnya ia menulis kritiknya terhadap berbagai hal dengan sangat tajam dalam karya-karyanya.” Novel Mo Yan yang belum lama ini diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah Big Breasts and Wide Hips.
Feng Yi membacakan esainya, Berjalan Menyusuri Sungai, mengisahkan pengalaman ayahnya yang menjadi perwira Tentara Pembebasan Rakyat dan menulis artikel untuk sebuah suratkabar yang dicap “Trotskyisme”, doktrin sosialisme yang berbeda dengan doktrin Mao.
Acara ini digagas oleh Perhimpunan Penulis Indonesia-Tionghoa bekerja sama dengan Salihara. Pemerintah Tiongkok mendukung lima penulis negeri itu untuk mengenalkan sastra dan budaya Tiongkok. Sebelum mampir di Jakarta, mereka melakukan kegiatan serupa di Malaysia dan Filipina.
Sastrawan Zen Hae sempat bertanya, “Apakah partai atau pemerintah tidak menyensor karya-karya para penulis?” Yang Ke menjawab bahwa karya-karya sastra lebih bebas. Tapi pemerintah lebih ketat mengawasi film. Sebab film dapat diterima oleh khalayak yang lebih luas dan tidak memerlukan tingkat wawasan yang tinggi untuk mencernanya, berbeda dengan karya sastra yang beredar lebih banyak di kalangan intelektual. Film dapat mempengaruhi dengan lebih cepat. Namun, film-film yang sempat dilarang pemerintah biasanya bisa beredar lagi. Pemerintah Tiongkok mendukung film-film karya sutradara negara tersebut untuk mendapat apresiasi dari masyarakat dunia. Foto: Dok. The Telegraph.