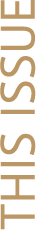Mendengar Cerita Sedih dan Nyanyian Paus dari Okinawa
Saya menginap di sebuah hotel kecil, yang letaknya tak jauh dari pasar. Udara sejuk di pengujung musim dingin menyertai langkah-langkah saya menelusuri kota Naha, yang dimulai dari pasar itu. Para sejarawan percaya bahwa pasar adalah cikal-bakal sebuah kota, meskipun keindahan yang diharapkan para penyair jarang muncul dari sini. Di kios penjual ikan, beberapa ekor ikan bersisik biru terbaring dengan mata melotot di meja pajang. Sukar membayangkan ikan dengan warna biru cemerlang nan indah berakhir dalam panci. Selama ini saya melihat ikan-ikan biru berenang dalam akuarium, bukan untuk dijual dan dimasak.
Sehari sebelumnya, 15 Maret 2005, pesawat yang membawa saya mendarat di Okinawa, sebuah provinsi kepulauan di Jepang. Dari bandara Haneda di Tokyo, dibutuhkan waktu terbang 2 jam 5 menit untuk sampai di bandara Naha. Jarak dari Tokyo ke Naha sejauh 965 mil atau 1.553 kilometer. Cuaca tidak begitu baik. Petir menyambar-nyambar. Pesawat terguncang keras beberapa kali. Di Naha, saya akan menghadiri serangkaian pertemuan yang membahas isu-isu regional, yang meliputi kebudayaan, ekonomi dan sistem pertahanan. Selebihnya adalah kesempatan untuk berimajinasi dan menulis cerita.
Di tahun itu, Okinawa bukan tempat kunjungan yang populer. Banyak orang Jepang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di Okinawa. “Pemandangan alamnya indah, tapi sangat berbeda dengan Jepang yang kamu lihat,” tutur seorang teman di Tokyo.
Tidak ada kemacetan di jalanan kota Naha. Rumah-rumah warga di sini lebih mirip rumah-rumah orang di Jakarta. Bedanya, di depan atau di atas sejumlah rumah itu tampak patung shisa, makhluk mitologi berwujud setengah anjing dan setengah singa. Fungsinya untuk melindungi para penghuni rumah secara spiritualistik. Shisa menjadi simbol khas Okinawa, yang juga mewujud dalam berbagai jenis cinderamata untuk pelancong. Menurut cerita rakyat, dulu seorang pendatang dari Tiongkok menghadiahi benda berbentuk unik ini kepada kaisar Ryukyu dan kekuatannya telah melindungi rakyat dari serangan naga yang menguasai laut mereka.
Dalam satu hal, situasi di Okinawa mirip dengan situasi di Aceh dulu, provinsi di ujung barat Indonesia. Sebagian orang Aceh pernah merasa bukan orang Indonesia, seperti sebagian orang Okinawa merasa mereka bukan orang Jepang. Seorang profesor sejarah di Naha bersaksi dalam diskusi kami dan barangkali membuat merah telinga sebagian intelektual Jepang yang hadir, “Sesungguhnya orang Okinawa dijajah orang Jepang.”
Pangkalan militer Amerika yang terbesar di Pasifik juga berada di Okinawa dan menambah ketegangan itu. Pangkalan tersebut berdiri begitu Perang Pasifik berakhir pada 1945 ketika Jepang takluk kepada Sekutu. Luasnya menyita sepertiga luas Okinawa. Banyak masalah muncul gara-gara kehadiran pangkalan ini. Tak lama sebelum saya datang, tiga tentara baru saja dipulangkan ke negaranya, karena memperkosa seorang remaja perempuan. Mereka tidak dipecat, melainkan dipindahtugaskan ke tempat lain. Salah satu sisi bangunan Universitas Ryukyu menghitam akibat helikopter militer jatuh hingga terbakar di situ. Seorang dosen bercerita kepada saya bahwa pihak militer Amerika hanya bertanya berapa banyak pohon yang terbakar dan harus diganti akibat insiden tersebut, bukan menanyakan berapa banyak manusia yang menjadi korban. Beruntung tidak ada jiwa yang terenggut. Satu desa pernah hangus gara-gara pesawat jatuh. Di desa lain, air sumur tak dapat diminum lagi akibat tercemar kadar minyak yang tinggi dari aktivitas militer di pangkalan.
Di kota ini saya menyaksikan betapa berat upaya manusia mempertahankan tanahnya dan martabatnya saat datang ke museum perdamaian. Kuburan massal terletak di taman museum. Nama-nama penduduk yang gugur saat Perang Pasifik terpahat di batu-batu granit hitam dalam huruf kanji. Orang-orang Okinawa memilih terjun ke Samudra Pasifik ketimbang menyerah pada serdadu Jepang. Sementara serdadu Jepang yang tergabung dalam aliansi negara-negara fasis dengan Jerman dan Italia berperang melawan Amerika, Rusia dan Inggris. Jepang menyerah ketika Hiroshima dibom. Tepat di belakang museum tersebut, orang-orang Okinawa yang rela kehilangan nyawa daripada takluk itu dulu mengakhiri hidup mereka. Laut Pasifik menggelora, ombaknya berdebur, batu-batu karang menunggu, jauh di bawah sana.
Setelah mendengar cerita-cerita sedih, tiba saatnya menikmati wisata laut di kepulauan yang indah ini. Untuk mencapai Pulau Zamami, salah satu pulau wisata, pelancong harus naik kapal cepat dari pelabuhan Tomari. Sebuah kapal cepat besar dengan nama tertera pada tubuhnya, Queen Zamami, sudah menunggu. Udara benar-benar dingin. Sebagian penumpang sudah duduk di kursi masing-masing saat saya naik dan mencari kursi. Tak berapa lama kapal cepat ini mulai melaju dan akhirnya melompat-lompat seperti ikan terbang yang bermain-main dengan gelombang. Saya merasa senang. Belum pernah saya naik kapal yang bisa melompat setinggi ini. Jepang sangat maju dalam teknologi, pikir saya, takjub. Setelah hampir 20 menit kapal meluncur di laut, tiba-tiba nakhoda memberi pengumuman dalam Bahasa Jepang. Katanya, kami akan kembali lagi ke pelabuhan Tomari. Rupanya lompatan-lompatan itu dampak dari kerusakan mesin. Di pelabuhan, semua penumpang dipindahkan ke kapal cepat lain.
Di Pulau Zamami, saya menginap di sebuah bungalow yang terletak di muka teluk yang tenang. Pantainya berpasir putih, sedangkan air laut terlihat biru jernih. Di pagi hari terdengar jeritan burung elang yang terbang melintas di atas hutan di samping bungalow, bersahut-sahutan dengan gemuruh laut. Tempat ini cocok bagi orang-orang yang membutuhkan kesunyian untuk berkarya. Saya pun mulai menulis buku Seekor Burung Kecil Biru di Naha di sini.
Suatu hari saya memutuskan pergi menonton atraksi ikan paus. Para pelancong harus naik kapal cepat ke tengah laut. Semua orang diminta mengenakan jaket pelampung, bersiap untuk berburu ikan paus seperti Kapten Ahab dalam novel karya Herman Melville Moby Dick, tetapi tanpa harpun. Rupanya ikan-ikan paus bermigrasi ke Pasifik dari kutub untuk mencari suhu yang lebih hangat. Kapal yang kami tumpangi terombang-ambing di laut. Nakhoda kapal berkata agar penumpang bersabar menunggu ikan paus muncul. Ikan itu bisa menyanyi, katanya. Sekitar 15 menit kemudian, sesuatu menyeruak ke permukaan laut, seperti sepasang kelopak bunga raksasa. Ekor ikan paus! Setelah itu tampak dua ekor ikan paus bercengkrama di air, besar dan kecil, ibu dan anak. Terdengar pula suara mencicit-cicit… Nah, itu nyanyian ikan yang dimaksud.
Di malam sebelum meninggalkan Naha keesokan harinya, saya menghabiskan waktu di sebuah karaoke bersama beberapa teman baru. Ada awamori, arak khas Okinawa, ada bir. Terdengar seseorang melantunkan sebuah lagu lama dari grup musik ABBA, Dancing Queen. Saya buru-buru menari. Meskipun setelah ini saya masih beberapa kali pergi ke Jepang, pengalaman di Okinawa paling mengesankan. (LC) Foto: Dok. Jpninfo, Dok. Japan Times
Sehari sebelumnya, 15 Maret 2005, pesawat yang membawa saya mendarat di Okinawa, sebuah provinsi kepulauan di Jepang. Dari bandara Haneda di Tokyo, dibutuhkan waktu terbang 2 jam 5 menit untuk sampai di bandara Naha. Jarak dari Tokyo ke Naha sejauh 965 mil atau 1.553 kilometer. Cuaca tidak begitu baik. Petir menyambar-nyambar. Pesawat terguncang keras beberapa kali. Di Naha, saya akan menghadiri serangkaian pertemuan yang membahas isu-isu regional, yang meliputi kebudayaan, ekonomi dan sistem pertahanan. Selebihnya adalah kesempatan untuk berimajinasi dan menulis cerita.
Di tahun itu, Okinawa bukan tempat kunjungan yang populer. Banyak orang Jepang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di Okinawa. “Pemandangan alamnya indah, tapi sangat berbeda dengan Jepang yang kamu lihat,” tutur seorang teman di Tokyo.
Tidak ada kemacetan di jalanan kota Naha. Rumah-rumah warga di sini lebih mirip rumah-rumah orang di Jakarta. Bedanya, di depan atau di atas sejumlah rumah itu tampak patung shisa, makhluk mitologi berwujud setengah anjing dan setengah singa. Fungsinya untuk melindungi para penghuni rumah secara spiritualistik. Shisa menjadi simbol khas Okinawa, yang juga mewujud dalam berbagai jenis cinderamata untuk pelancong. Menurut cerita rakyat, dulu seorang pendatang dari Tiongkok menghadiahi benda berbentuk unik ini kepada kaisar Ryukyu dan kekuatannya telah melindungi rakyat dari serangan naga yang menguasai laut mereka.
Dalam satu hal, situasi di Okinawa mirip dengan situasi di Aceh dulu, provinsi di ujung barat Indonesia. Sebagian orang Aceh pernah merasa bukan orang Indonesia, seperti sebagian orang Okinawa merasa mereka bukan orang Jepang. Seorang profesor sejarah di Naha bersaksi dalam diskusi kami dan barangkali membuat merah telinga sebagian intelektual Jepang yang hadir, “Sesungguhnya orang Okinawa dijajah orang Jepang.”
Pangkalan militer Amerika yang terbesar di Pasifik juga berada di Okinawa dan menambah ketegangan itu. Pangkalan tersebut berdiri begitu Perang Pasifik berakhir pada 1945 ketika Jepang takluk kepada Sekutu. Luasnya menyita sepertiga luas Okinawa. Banyak masalah muncul gara-gara kehadiran pangkalan ini. Tak lama sebelum saya datang, tiga tentara baru saja dipulangkan ke negaranya, karena memperkosa seorang remaja perempuan. Mereka tidak dipecat, melainkan dipindahtugaskan ke tempat lain. Salah satu sisi bangunan Universitas Ryukyu menghitam akibat helikopter militer jatuh hingga terbakar di situ. Seorang dosen bercerita kepada saya bahwa pihak militer Amerika hanya bertanya berapa banyak pohon yang terbakar dan harus diganti akibat insiden tersebut, bukan menanyakan berapa banyak manusia yang menjadi korban. Beruntung tidak ada jiwa yang terenggut. Satu desa pernah hangus gara-gara pesawat jatuh. Di desa lain, air sumur tak dapat diminum lagi akibat tercemar kadar minyak yang tinggi dari aktivitas militer di pangkalan.
Di kota ini saya menyaksikan betapa berat upaya manusia mempertahankan tanahnya dan martabatnya saat datang ke museum perdamaian. Kuburan massal terletak di taman museum. Nama-nama penduduk yang gugur saat Perang Pasifik terpahat di batu-batu granit hitam dalam huruf kanji. Orang-orang Okinawa memilih terjun ke Samudra Pasifik ketimbang menyerah pada serdadu Jepang. Sementara serdadu Jepang yang tergabung dalam aliansi negara-negara fasis dengan Jerman dan Italia berperang melawan Amerika, Rusia dan Inggris. Jepang menyerah ketika Hiroshima dibom. Tepat di belakang museum tersebut, orang-orang Okinawa yang rela kehilangan nyawa daripada takluk itu dulu mengakhiri hidup mereka. Laut Pasifik menggelora, ombaknya berdebur, batu-batu karang menunggu, jauh di bawah sana.
Setelah mendengar cerita-cerita sedih, tiba saatnya menikmati wisata laut di kepulauan yang indah ini. Untuk mencapai Pulau Zamami, salah satu pulau wisata, pelancong harus naik kapal cepat dari pelabuhan Tomari. Sebuah kapal cepat besar dengan nama tertera pada tubuhnya, Queen Zamami, sudah menunggu. Udara benar-benar dingin. Sebagian penumpang sudah duduk di kursi masing-masing saat saya naik dan mencari kursi. Tak berapa lama kapal cepat ini mulai melaju dan akhirnya melompat-lompat seperti ikan terbang yang bermain-main dengan gelombang. Saya merasa senang. Belum pernah saya naik kapal yang bisa melompat setinggi ini. Jepang sangat maju dalam teknologi, pikir saya, takjub. Setelah hampir 20 menit kapal meluncur di laut, tiba-tiba nakhoda memberi pengumuman dalam Bahasa Jepang. Katanya, kami akan kembali lagi ke pelabuhan Tomari. Rupanya lompatan-lompatan itu dampak dari kerusakan mesin. Di pelabuhan, semua penumpang dipindahkan ke kapal cepat lain.
Di Pulau Zamami, saya menginap di sebuah bungalow yang terletak di muka teluk yang tenang. Pantainya berpasir putih, sedangkan air laut terlihat biru jernih. Di pagi hari terdengar jeritan burung elang yang terbang melintas di atas hutan di samping bungalow, bersahut-sahutan dengan gemuruh laut. Tempat ini cocok bagi orang-orang yang membutuhkan kesunyian untuk berkarya. Saya pun mulai menulis buku Seekor Burung Kecil Biru di Naha di sini.
Suatu hari saya memutuskan pergi menonton atraksi ikan paus. Para pelancong harus naik kapal cepat ke tengah laut. Semua orang diminta mengenakan jaket pelampung, bersiap untuk berburu ikan paus seperti Kapten Ahab dalam novel karya Herman Melville Moby Dick, tetapi tanpa harpun. Rupanya ikan-ikan paus bermigrasi ke Pasifik dari kutub untuk mencari suhu yang lebih hangat. Kapal yang kami tumpangi terombang-ambing di laut. Nakhoda kapal berkata agar penumpang bersabar menunggu ikan paus muncul. Ikan itu bisa menyanyi, katanya. Sekitar 15 menit kemudian, sesuatu menyeruak ke permukaan laut, seperti sepasang kelopak bunga raksasa. Ekor ikan paus! Setelah itu tampak dua ekor ikan paus bercengkrama di air, besar dan kecil, ibu dan anak. Terdengar pula suara mencicit-cicit… Nah, itu nyanyian ikan yang dimaksud.
Di malam sebelum meninggalkan Naha keesokan harinya, saya menghabiskan waktu di sebuah karaoke bersama beberapa teman baru. Ada awamori, arak khas Okinawa, ada bir. Terdengar seseorang melantunkan sebuah lagu lama dari grup musik ABBA, Dancing Queen. Saya buru-buru menari. Meskipun setelah ini saya masih beberapa kali pergi ke Jepang, pengalaman di Okinawa paling mengesankan. (LC) Foto: Dok. Jpninfo, Dok. Japan Times