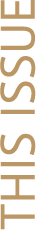Mengenal Mode Tanpa Musim

Buah bibir yang mengemuka selepas penyelenggaraan fashion week koleksi musim dingin 2016 di empat kota mode dunia pada awal tahun ini tak lagi bekisar pada bongkar-pasang pemimpin kreatif di beberapa merek tersohor. Bukan pula figur mana yang paling menonjol di arena street style. Apalagi perdebatan remeh-temeh tentang siapa catwalk darling yang paling laris membuka atau menutup show. Bukan.
Rumor hangat yang sedang ramai diungkit dan menuai argumentasi kali ini adalah menyoal pergeseran fungsi fashion week dan mekanisme baru see-now-buy-immediately yang ramai digadang oleh sejumlah desainer dan rumah mode raksasa. Menjadi alasan merek-merek besar untuk memberikan produk mereka ‘sesegera mungkin’ ke pasar? Sekadar eksperimen atas kejenuhan pola fashion week yang dinilai tak lagi relevan? Atau komitmen untuk menjauhkan diri dari jiplakan desain yang kian agresif?
MODE DAN BISNIS ‘CEPAT SAJI’
Sebelum jauh berapi-api menggali segala hipotesa dari fenomena di atas, ada baiknya jika kita mundur sejenak dan melihat fondasi yang menjadi landasan mengapa gelaran pekan mode (New York, London, Milan, Paris) begitu krusial dan sangat dituankan. Kembali ke awal abad 20, fashion show kala itu diadakan terutama bagi para buyer. Melalui pergelaran busana, buyer dimungkinkan untuk melihat koleksi sang desainer dan mengajukan order akan produk yang mereka anggap sesuai selera pasar. Adanya pesanan dari buyer tak ayal memudahkan ‘pekerjaan rumah’ para desainer. Melalui sistem tersebut, desainer bisa mengetahui dan membuat estimasi anggaran serta timeline produksi yang lebih jelas dan terarah. Para editor mode yang pula menikmati fashion show juga memegang fungsi yang kurang-lebih serupa. Meski ‘timbal-balik’ bukan berupa order produk, namun para editor mode inilah yang kemudian melakukan kurasi dan mengulas atau memuat key pieces yang dijagokan dari masing-masing rumah mode. Dengan begitu, saat seluruh produksi selesai dan produk akhirnya masuk di berbagai butik dan department store, ulasan mengenai koleksi dari merek-merek tersebut sudah tersedia lengkap di berbagai media. Menciptakan excitement tersendiri akan apa yang tren di tiap musimnya.
Namun di sepanjang abad ke-21 ini, perubahan sedikit-banyak mulai terjadi. Teknologi informasi yang bergerak cepat mau tak mau mendorong sejumlah merek mengubah model bisnis mereka untuk tetap relevan dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dari fenomena blogger dan “artis” dunia maya, menjamurnya media online, hingga era live streaming yang memungkinkan siapapun melihat koleksi teranyar suatu brand secara cepat dan seketika. Koleksi yang seyogyanya baru tersedia di pasar sekurangnya dalam empat bulan setelah dipresentasikan.
Rentang waktu antara jadwal show dan ketersediaan produk di pasaran ini lantas memunculkan sebuah dilema bagi banyak high-end brand. Pasalnya, jeda tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk mengopi berbagai desain produk mereka. Proses kreatif yang ‘termakan’ sistem pakem jadwal fashion week inilah yang kemudian mendorong lahirnya pemikiran baru di industri mode, yaitu adaptasi pada model bisnis real-time fashion.
Kehebohan dimulai pada gelaran fashion week di awal tahun ini (untuk koleksi musim dingin 2016), kala Burberry mengumumkan akan meluncurkan sistem baru see-now-buy-immediately pada koleksi busana wanita dan pria mereka per bulan September mendatang. Berbarengan dengan keputusan Christopher Bailey untuk membuat show yang tak lagi memberi rujukan akan musim dari koleksi yang ditampilkannya (seasonless collection).
Perbincangan kian panas tatkala semakin banyak desainer yang mengumumkan keputusan mereka mengadopsi model bisnis baru terkait waktu show dan waktu dilansirnya produk. Tom Ford salah satunya. Membatalkan show koleksi musim dinginnya di New York Fashion Week, Ford memutuskan memundurkan show-nya tersebut ke fashion week berikutnya di bulan September, sesuai atau berdekatan dengan waktu lansirnya koleksi musim dingin di butiknya nanti. Dalam siaran persnya, Tom Ford menyebutkan bahwasanya di dunia yang sekarang serba cepat dan segera, cara konvensional melakukan fashion show empat bulan sebelum barang tersedia bagi pelanggan adalah sebuah gagasan usang yang tak lagi masuk akal.
Sedikit berbeda dari Tom Ford, desainer Tommy Hilfiger memilih tetap mengadakan fashion show koleksi musim dinginnya di New York Fashion Week, pada Februari silam. Namun, alih-alih menampilkan koleksi musim panas 2017 pada September mendatang, Hilfiger justru mempresentasikan koleksi kolaborasi dengan model Gigi Hadid. Koleksi musim panas Tommy Hilfiger sendiri baru akan ia presentasikan pada awal 2017, di mana koleksi yang dipentaskan akan langsung tersedia di butik-butiknya.
Langkah yang sama sebenarnya sudah ditempuh oleh Matthew Williamson yang telah mengadopsi model real-time fashion sejak kuartal pertama tahun 2015, dan kini Williamson lebih berfokus membangun labelnya lewat platform online. Bergabungnya label Vetements untuk melakukan kebijakan bisnis yang sama pun mematahkan anggapan jika fenomena real-time fashion hanya didominasi oleh desainer yang berbasis di Amerika, layaknya Rebecca Minkoff, Thakoon, dan Michael Kors.
MASA DEPAN MODE?
Pertanyaan selanjutnya. Apakah hal ini lantas mengubah pakem struktur dan fungsi fashion week? Ah, rasanya terlalu dini untuk menyimpulkannya. Namun yang pasti, terdapat banyak pertimbangan ketika sebuah brand memutuskan untuk menjual langsung produk yang baru saja mereka presentasikan. Beberapa mungkin ingin meminimalisir pengopian desain. Adapula, Tom Ford misalnya, yang ingin memanfaatkan momentum hype selepas fashion show. Namun tak sedikit pula—Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, dan kebanyakan desainer berbasis di Amerika misalnya—yang memang tak memiliki kendala untuk memproduksi barang mereka dengan cepat karena kemudahan akses dengan pabrik rekanan.
Global network dari jaringan butik dan kekuatan finansial untuk membeli bahan serta menyimpannya tentu dimiliki oleh hampir seluruh high-end brand raksasa. Tapi bagaimana dengan desainer yang punya lokasi jauh dari rekanan pabrik mereka? Layaknya yang umum dialami oleh banyak brand Eropa. Misalnya saja, sebuah brand berbasis di Swedia, dengan pabrik material kulit di Florence, Italia; pabrik bulu domba di Skotlandia; dan pemasok bahan baku lainnya yang berada jauh di Madrid, Spanyol. Jika brand besar Eropa saja akan dibuat kelimpungan dengan hal ini, apa yang akan terjadi dengan label-label independen yang tidak tergabung dalam korporasi raksasa macam Kering atau LVMH? Dapatkah mereka berkompetisi dan memproduksi seluruh barangnya dalam rentang waktu ‘segera’ seperti model bisnis see-now-buy-immediately? Mampukah mereka memproduksi koleksinya langsung dalam kuantitas besar sebelum menerima order dari para buyer?
Dalam wawancara dengan New York Times, J.W. Anderson memberikan tanggapannya. Menurut Anderson, dalam banyak kasus masyarakat membutuhkan waktu untuk mencerna konsep dan ide dari sebuah koleksi, serta membiasakan diri dengan siluet yang dibawa oleh masing-masing brand. Jika koleksi tersebut masuk di toko sehari setelah peragaan busana, bukan tidak mungkin koleksi tersebut akan tenggelam akibat ketidakyakinan masyarakat. Karena bagaimana pun, tak semua brand hanya melansir kemeja putih atau rok pensil hitam, bukan? Begitu banyak brand yang menggarap konsep busana tak lazim yang mengharuskan masyarakat mencerna dengan matang sebelum memutuskan untuk membeli. Pertanyaan kemudian berkembang. Yakinkah pelaku dunia mode jika seluruh instrumen yang terlibat di dalamnya siap dengan model bisnis baru ini? Apakah ungkapan ‘yang tidak siap akan tersingkir’ adalah harga mati bagi label-label muda independen? Gelaran fashion week musim depan akan menjadi babak baru topik ini!
TEKS (Ruben William) FOTO: Dok. Burberry, Tommy Hilfiger, Tom Ford
Rumor hangat yang sedang ramai diungkit dan menuai argumentasi kali ini adalah menyoal pergeseran fungsi fashion week dan mekanisme baru see-now-buy-immediately yang ramai digadang oleh sejumlah desainer dan rumah mode raksasa. Menjadi alasan merek-merek besar untuk memberikan produk mereka ‘sesegera mungkin’ ke pasar? Sekadar eksperimen atas kejenuhan pola fashion week yang dinilai tak lagi relevan? Atau komitmen untuk menjauhkan diri dari jiplakan desain yang kian agresif?
MODE DAN BISNIS ‘CEPAT SAJI’
Sebelum jauh berapi-api menggali segala hipotesa dari fenomena di atas, ada baiknya jika kita mundur sejenak dan melihat fondasi yang menjadi landasan mengapa gelaran pekan mode (New York, London, Milan, Paris) begitu krusial dan sangat dituankan. Kembali ke awal abad 20, fashion show kala itu diadakan terutama bagi para buyer. Melalui pergelaran busana, buyer dimungkinkan untuk melihat koleksi sang desainer dan mengajukan order akan produk yang mereka anggap sesuai selera pasar. Adanya pesanan dari buyer tak ayal memudahkan ‘pekerjaan rumah’ para desainer. Melalui sistem tersebut, desainer bisa mengetahui dan membuat estimasi anggaran serta timeline produksi yang lebih jelas dan terarah. Para editor mode yang pula menikmati fashion show juga memegang fungsi yang kurang-lebih serupa. Meski ‘timbal-balik’ bukan berupa order produk, namun para editor mode inilah yang kemudian melakukan kurasi dan mengulas atau memuat key pieces yang dijagokan dari masing-masing rumah mode. Dengan begitu, saat seluruh produksi selesai dan produk akhirnya masuk di berbagai butik dan department store, ulasan mengenai koleksi dari merek-merek tersebut sudah tersedia lengkap di berbagai media. Menciptakan excitement tersendiri akan apa yang tren di tiap musimnya.
Namun di sepanjang abad ke-21 ini, perubahan sedikit-banyak mulai terjadi. Teknologi informasi yang bergerak cepat mau tak mau mendorong sejumlah merek mengubah model bisnis mereka untuk tetap relevan dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dari fenomena blogger dan “artis” dunia maya, menjamurnya media online, hingga era live streaming yang memungkinkan siapapun melihat koleksi teranyar suatu brand secara cepat dan seketika. Koleksi yang seyogyanya baru tersedia di pasar sekurangnya dalam empat bulan setelah dipresentasikan.
Rentang waktu antara jadwal show dan ketersediaan produk di pasaran ini lantas memunculkan sebuah dilema bagi banyak high-end brand. Pasalnya, jeda tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab untuk mengopi berbagai desain produk mereka. Proses kreatif yang ‘termakan’ sistem pakem jadwal fashion week inilah yang kemudian mendorong lahirnya pemikiran baru di industri mode, yaitu adaptasi pada model bisnis real-time fashion.
Kehebohan dimulai pada gelaran fashion week di awal tahun ini (untuk koleksi musim dingin 2016), kala Burberry mengumumkan akan meluncurkan sistem baru see-now-buy-immediately pada koleksi busana wanita dan pria mereka per bulan September mendatang. Berbarengan dengan keputusan Christopher Bailey untuk membuat show yang tak lagi memberi rujukan akan musim dari koleksi yang ditampilkannya (seasonless collection).
Perbincangan kian panas tatkala semakin banyak desainer yang mengumumkan keputusan mereka mengadopsi model bisnis baru terkait waktu show dan waktu dilansirnya produk. Tom Ford salah satunya. Membatalkan show koleksi musim dinginnya di New York Fashion Week, Ford memutuskan memundurkan show-nya tersebut ke fashion week berikutnya di bulan September, sesuai atau berdekatan dengan waktu lansirnya koleksi musim dingin di butiknya nanti. Dalam siaran persnya, Tom Ford menyebutkan bahwasanya di dunia yang sekarang serba cepat dan segera, cara konvensional melakukan fashion show empat bulan sebelum barang tersedia bagi pelanggan adalah sebuah gagasan usang yang tak lagi masuk akal.
Sedikit berbeda dari Tom Ford, desainer Tommy Hilfiger memilih tetap mengadakan fashion show koleksi musim dinginnya di New York Fashion Week, pada Februari silam. Namun, alih-alih menampilkan koleksi musim panas 2017 pada September mendatang, Hilfiger justru mempresentasikan koleksi kolaborasi dengan model Gigi Hadid. Koleksi musim panas Tommy Hilfiger sendiri baru akan ia presentasikan pada awal 2017, di mana koleksi yang dipentaskan akan langsung tersedia di butik-butiknya.
Langkah yang sama sebenarnya sudah ditempuh oleh Matthew Williamson yang telah mengadopsi model real-time fashion sejak kuartal pertama tahun 2015, dan kini Williamson lebih berfokus membangun labelnya lewat platform online. Bergabungnya label Vetements untuk melakukan kebijakan bisnis yang sama pun mematahkan anggapan jika fenomena real-time fashion hanya didominasi oleh desainer yang berbasis di Amerika, layaknya Rebecca Minkoff, Thakoon, dan Michael Kors.
MASA DEPAN MODE?
Pertanyaan selanjutnya. Apakah hal ini lantas mengubah pakem struktur dan fungsi fashion week? Ah, rasanya terlalu dini untuk menyimpulkannya. Namun yang pasti, terdapat banyak pertimbangan ketika sebuah brand memutuskan untuk menjual langsung produk yang baru saja mereka presentasikan. Beberapa mungkin ingin meminimalisir pengopian desain. Adapula, Tom Ford misalnya, yang ingin memanfaatkan momentum hype selepas fashion show. Namun tak sedikit pula—Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, dan kebanyakan desainer berbasis di Amerika misalnya—yang memang tak memiliki kendala untuk memproduksi barang mereka dengan cepat karena kemudahan akses dengan pabrik rekanan.
Global network dari jaringan butik dan kekuatan finansial untuk membeli bahan serta menyimpannya tentu dimiliki oleh hampir seluruh high-end brand raksasa. Tapi bagaimana dengan desainer yang punya lokasi jauh dari rekanan pabrik mereka? Layaknya yang umum dialami oleh banyak brand Eropa. Misalnya saja, sebuah brand berbasis di Swedia, dengan pabrik material kulit di Florence, Italia; pabrik bulu domba di Skotlandia; dan pemasok bahan baku lainnya yang berada jauh di Madrid, Spanyol. Jika brand besar Eropa saja akan dibuat kelimpungan dengan hal ini, apa yang akan terjadi dengan label-label independen yang tidak tergabung dalam korporasi raksasa macam Kering atau LVMH? Dapatkah mereka berkompetisi dan memproduksi seluruh barangnya dalam rentang waktu ‘segera’ seperti model bisnis see-now-buy-immediately? Mampukah mereka memproduksi koleksinya langsung dalam kuantitas besar sebelum menerima order dari para buyer?
Dalam wawancara dengan New York Times, J.W. Anderson memberikan tanggapannya. Menurut Anderson, dalam banyak kasus masyarakat membutuhkan waktu untuk mencerna konsep dan ide dari sebuah koleksi, serta membiasakan diri dengan siluet yang dibawa oleh masing-masing brand. Jika koleksi tersebut masuk di toko sehari setelah peragaan busana, bukan tidak mungkin koleksi tersebut akan tenggelam akibat ketidakyakinan masyarakat. Karena bagaimana pun, tak semua brand hanya melansir kemeja putih atau rok pensil hitam, bukan? Begitu banyak brand yang menggarap konsep busana tak lazim yang mengharuskan masyarakat mencerna dengan matang sebelum memutuskan untuk membeli. Pertanyaan kemudian berkembang. Yakinkah pelaku dunia mode jika seluruh instrumen yang terlibat di dalamnya siap dengan model bisnis baru ini? Apakah ungkapan ‘yang tidak siap akan tersingkir’ adalah harga mati bagi label-label muda independen? Gelaran fashion week musim depan akan menjadi babak baru topik ini!
TEKS (Ruben William) FOTO: Dok. Burberry, Tommy Hilfiger, Tom Ford